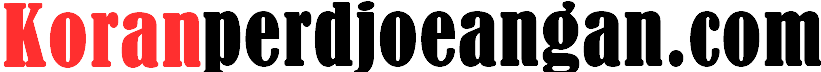Jakarta, KPonline – Padahal kami melakukan kritik untuk kebaikan. Tetapi justru kami dituduh memecah belah dan menghancurkan organisasi.”
Kalimat itu berulangkali saya dengar dari orang yang gemar menyampaikan kritik terhadap organisasi.
Reaksi saya yang pertama saat mendengar itu, tentu saja tertawa. Rupanya tukang kritik pun nggak suka dikritik.
Tukang kritik pun nggak mau dikritik jika apa yang ia lakukan bisa memecah belah organisasi. Baper juga dia.
Jadi nggak boleh mengkritik nih?
Tenang dulu. Ini bukan soal mau atau nggak mau dikritik. Ini soal tanggungjawab. Bahwa antara kita sebenarnya adalah saudara. Bukan orang jauh.
Kalaulah ada yang perlu diperbaiki, mari sama-sama memperbaiki. Kalaulah ada yang salah, mari sama-sama kita betulkan.
Jangan hanya menyalah-nyalahkan, tapi kemudian ongkang-ongkang kaki sambil mencari-cari kesalahan — dengan dalih kritik.
Lalu ketika dikritik balik, jika kritiknya itu justru akan memecah belah, nggak terima.
Sebenarnya ya nggak bakal ada yang pecah karena kritik. Paling banter yang dikritik akan emosi lalu mengkritik balik, “Hei, bung. Apa yang sudah Anda lakukan untuk memajukan gerakan ini? Gue sudah capek-capek kerja lo datang-datang bisanya nyinyir aja.”
Jangan marah kalau ada yang mengatakan demikian. Anggap saja itu sebagai kritik juga buat kita yang suka mengkritik. Toh tujuannya baik. Agar Anda jangan hanya bisa mengkritik. Tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, tidak hanya berisik di belakang.
* * *
Kami di Media Perdjoeangan, hampir selalu saling kritik.
Redaktur eksekutif kami yang berada di Batam, bung Suhari, sering uring-uringan jika ada kontributor yang mengirimkan tulisan acak-acakan. Misal penempatan huruf kapital yang tidak pada tempatnya, atau saat kami menyusun kalimat yang sulit dipahami.
Kami yang dikritik biasanya akan mengucapkan terima kasih. Sudah diingatkan. Lalu dalam tulisan berikutnya, tidak ada lagi kesalahan.
Meskipun ada juga yang meng-kick balik. “Memang sengaja nulisnya saya bikin salah. Mau nge-tes bung Redakur, sebenarnya tulisan kontributor dibaca ulang atau tidak sebelum dipublish.”
Kami tahu, redaktur menyampaikan kritik terhadap tulisan kami karena ingin ada perbaikan di kemudian hari. Lagipula dia sudah 24 jam mengawal setiap tulisan yang masuk. Sebelum mengkritik, sudah terlebih dahulu memberikan teladan tentang kerja-kerja yang benar.
Akan berbeda kalau yang melakukannya adalah orang yang tak pernah membuat karya. Pasti akan diserang balik. “Coba kau bikin sendiri satu artikel yang bener, jangan cuma bisa nyuruh…”
Begitulah. Di dunia kreatif, kritik adalah cara kita memberi apresiasi terhadap lahirnya sebuah karya.
Di bidang sastra, kegiatan kritik sastra pertama kali dilakukan oleh bangsa Yunani yang bernama Xenophanes dan Heraclitus. Mereka mengecam pujangga Yunani yang bernama Homerus yang gemar menceritakan kisah dewa-dewi.
Para pujangga Yunani menganggap karya-karya Homerus tentang kisah dewa-dewi tidak baik dan bohong. Peristiwa kritik sastra ini diikuti oleh kritikus-kritikus berikutnya di Yunani seperti Aristophanes ( 450-385 sM), Plato (427-347 sM), dan Aristoteles murid Plato (384-322 sM).
Buku tentang kritik sastra yang dianggap cukup lengkap dan merupakan sumber pengertian kritik sastra modern ialah karya Julius Caesar Scaliger (1484-1585) yang berjudul Criticus. Di dalamnya memuat tentang perbandingan antara pujangga-pujangga Yunani dan Latin dengan titik berat kepada pertimbangan, penyejajaran, dan penghakiman terhadap Homerus.
Kemudian muncul pula istilah criticism yang digunakan penyair Jhon Dryden (Inggris, 1677). Semenjak itu istilah criticism lebih banyak digunakan dari pada istilah critic karena dianggap memiliki pengertian yang lebih fleksibel.
Intinya, ada kriteria yang digunakan dalam kritik. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari kritikan tersebut merupakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya bersifat pendapat pribadi. Jika tidak, sesungguhnya kita sedang menebar benci. Bukan memperbaiki.